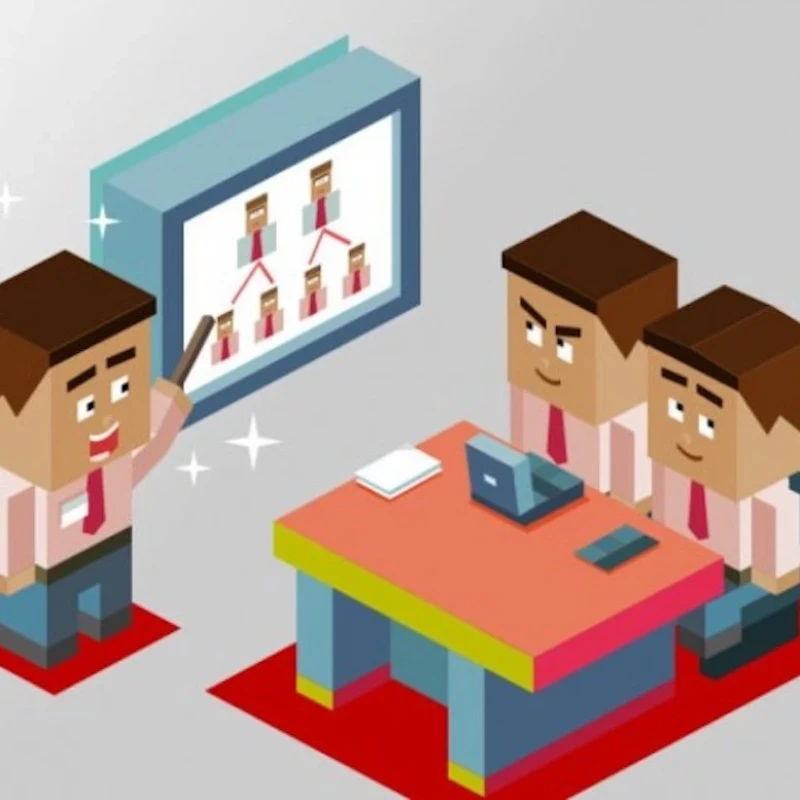“Orang kok semuanya seperti Oshin, ya?” celetuk saya kepada Syauqi.
Sore itu, rombongan short course PKUMI ke Hartford sedang transit di Bandara Internasional Narita Tokyo, Jepang. Setelah tujuh jam perjalanan udara dari Jakarta dan sepuluh jam selanjutnya menuju Los Angeles, Amerika Serikat.
Dengan waktu transit yang hanya sekitar satu jam, kami memilih untuk tinggal dan menunggu di bandara. Artinya, tidak sempat keluar bandara melihat sekilas lekuk tubuh Negeri Matahari Terbit tersebut. Namun, pengalaman di dalam bandara pun tidak kalah mengesankan.
Di dalam waiting room, tepat di depan pemeriksaan boarding pass, terhampar sekumpulan pramugari. Dengan memakai seragam yang serba aristokrat, mereka berjajar dan bersiap menunggu menit ketika satu per satu penumpang diverifikasi dan dipersilakan masuk.
Inilah pengalaman pertama saya melihat orang Jepang di negara Jepang. Rupa dan paras mereka hampir sama satu dengan lainnya. Tinggi, kulit putih cemerlang, berwajah tirus, dengan rambut yang diputar-lilit sedemikian rupa. Tentu saja dengan ciri yang satu ini; mata sipit yang dilingkupi katup mata yang bulat melandai.
Fikiran saya seketika meluncur ke satu figur yang saya lihat belasan tahun yang lalu; Oshin. Sosok perempuan kecil yang hidup dalam kemiskinan, yang kemudian tumbuh dewasa menjadi kaya raya dengan menjadi pemilik jaringan supermarket besar di Jepang.
Nama ‘Oshin’ itulah yang kemudian menjadi judul serial drama televisi yang mengisahkan kehidupannya tersebut. Oshin adalah satu cerita sukses telenovela Jepang yang merebut jutaaan pemirsa di seluruh dunia di akhir abad ke-20.
“Oshin?” respon Syauqi seakan tidak percaya bahwa saya mengenal sosok tersebut. “Itu berarti kamu sudah orang lama di dunia ini?” lanjutnya.
Saya pun membalas; “Kalau Anda tahu bahwa orang yang tahu Oshin itu orang lama, berarti ada kemungkinan Anda juga orang lama.” Kami pun tertawa kecil menyadari bahwa memang kita sudah cukup lama hidup di dunia ini.
Berdiri, melihat, dan merasakan langsung hawa udara negeri bernama Jepang adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab, hal yang sebelumnya hanya bercokol dalam pengetahuan dan imajinasi ternyata sekarang menjadi fakta yang bisa dilihat dengan kasat mata.
Sampai di sini pula, fikiran saya teringat pada penjelasan Prof. Dr. Quraish Shihab tentang tiga istilah dalam al-Qur’an yang saling berkelindan; ‘ilm al-yaqin, ‘ain al-yaqin, dan haqq al-yaqin.
‘Ilm al-Yaqin, ‘Ain al-Yaqin, dan Haqq al-Yaqin.
Ketiga frase di atas masing-masing muncul sekali dalam al-Qur’an, yaitu pada al-Takatsur ayat 5 (kalla law ta’lamun ‘ilm al-yaqin), al-Takatsur ayat 7 (tsumma latarawunnaha ‘ain al-yaqin), dan al-Waqi’ah ayat 95 (inna hadza lahuwa haqq al-yaqin).
Kata yaqin itu sendiri, menurut Prof Quraish Shihab, adalah “pembenaran hati yang sangat mantap terhadap sesuatu, sehingga tidak ada lagi sedikit kerancuan pun yang menyertainya – setelah sebelumnya kerancuan itu pernah dirasakan” (Tafsir al-Mishbah 13:585). Dengan menyandarkan tiga kata, yaitu ‘ilm (ilmu), ‘ain (penglihatan), dan haqq (hakikat), masing-masing pada kata yaqin, maka keyakinan itu sendiri dapat kemudian dikategorikan setidaknya pada tiga tingkatan; (1) keyakinan yang berdasar penalaran ilmu pengetahuan (’ilm al-yaqin), (2) keyakinan yang berdasar pada pengalaman indrawi (‘ain al-yaqin), dan (3) keyakinan sejati yang merupakan level tertinggi dari ketiga jenis keyakinan yang ada (haqq al-yaqin).
Jika selanjutnya keyakinan tersebut kita korespondensikan dengan pengetahuan, maka akan tampak di hadapan kita tiga tingkatan pengetahuan; pengetahuan nalar, pengetahuan indrawi, dan pengetahuan sejati.
Menalar ‘Ilm al-Yaqin
Sederhananya, ‘ilm al-yaqin adalah pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran akal. Quraish Shihab lebih lanjut memberikan contohnya; “Sebagai ilustrasi dapat dikatakan bahwa jika Anda membenarkan adanya kota yang bernama Kairo berdasar penuturan banyak orang – walau Anda sendiri belum pernah melihatnya — maka ini dapat dipersamakan dengan ‘Ilm al-Yaqīn.”
Meski sebelum transit di Jepang, dengan penalaran akal, saya dapat menarik satu kesimpulan bahwa negeri yang bernama Jepang memang nyata ada. Hal tersebut saya dapatkan dari orang-orang yang mengabarkan pernah ke Jepang, atau gambar-gambar di buku, majalah dan televisi yang memberitakan keberadaan segolongan manusia bermata sipit dengan beberapa ciri fisik lain berikut kebudayaan yang melekat pada diri mereka.
Atau bahkan memang ketika di sekolah menengah dulu, saya pernah bertemu langsung dengan orang Jepang. Pada titik ini, melalui berita dan fakta yang sulit untuk diragukan, penalaran akal menarik kesimpulan bahwa negeri bernama Jepang pasti ada.
Hanya saja, betapa pun itu sebuah kesimpulan, pengetahuan yang saya dapatkan belum sampai pada tingkatan yang sesungguhnya. Sebab, kenyataannya memang saya belum pernah menginjakkan kaki di negeri bernama Jepang tersebut. Pengetahuan jenis inilah yang kemudian disebut sebagai ‘ilm al-yaqin.
Dalam konteks al-Takatsur ayat 5, di mana di dalamnya tersebut redaksi "ilm al-yaqin", pengetahuan ‘ilm al-yaqin dapat berupa kepastian akan adanya neraka Jahim yang memang sudah sedari awal diberitakan di dunia ini. Terutama bagi mereka yang sering bermegah-megahan dalam harta dan keturunan yang dikaruniakan Tuhan.
Namun, sekali lagi, kepastian tersebut belum bersifat absolut. Sebab ia lebih dihasilkan dari penalaran akal. Dalam Hikmat al-Tashri’ wa Falsafatuhu, Ali Ahmad al-Jurjawi menyatakan bahwa adanya akhirat – di mana nikmat surga dan siksa neraka termasuk bagian darinya – sebagai hari pembalasan merupakan sesuatu yang logis.
Membuktikan ‘Ilm al-Yaqin dengan Akal
Jika keadilan adalah satu prinsip yang diterima secara universal, maka cukup masuk akal jika seharusnya memang ada satu masa setelah di dunia ini di mana segala balasan atas perbuatan manusia, baik atau buruk, akan ditunaikan seadil-adilnya.
Sebab, jika yang terjadi sebaliknya, lanjut al-Jurjawi, bagaimana dengan Hitler yang membunuh jutaan manusia sementara ia hanya mati sebab bunuh diri begitu saja. Apakah itu cukup adil bagi perbuatannya yang demikian keji?
Termasuk juga bagaimana dengan orang yang sedemikian dermawan dalam hidupnya. Yang seringkali mendonasikan hartanya di kotak amal sementara hal tersebut sama sekali tidak diketahui khalayak. Ia sendiri bahkan tidak tahu di halaman mana dalam lembaran kehidupannya perbuatan mulia tersebut dibalas oleh Tuhan.
Sebagian balasan memang sudah tersedia di dunia ini. Mereka yang berbuat baik pada dasarnya pun akan dibalas oleh orang lain dengan kebaikan. Sebagaimana mereka yang berbuat jahat pun akan menuai balasan atas kejahatannya. Namun pembalasan akhir yang setimpal atau bahkan seluas-luasnya baru akan diadakan di akhirat nanti. Akhirat merupakan tempat diselenggarakannya keadilan paripurna.
Dari sini, berdasarkan pada universalitas konsep keadilan, dapat dinyatakan bahwa keberadaan kehidupan akhirat adalah sesuatu yang secara nalar sangat mungkin – jika bukan pasti – terjadi. Dalam konteks Jepang, dengan adanya peta negeri bernama ‘Jepang’ yang melintang di sebelah timur daratan Cina sementara saya sendiri melihat ada orang yang mengaku dari negeri tersebut, maka saya bisa meyakini bahwa negeri tersebut memang benar-benar ada – meski belum pernah ke sana sebelumnya. Keyakinan inilah yang disebut sebagai ‘ilm al-yaqin.
Membuktikan ‘Ilm al-Yaqin dengan Khabar Shadiq
Selain akal, menurut Penulis, pengetahuan ‘ilm al-yaqin juga bisa didapatkan dari apa yang disebut khabar shadiq (true report), yaitu berita benar yang validitasnya dapat dipastikan. Dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam, Syed Naquib Al-Attas sekilas menyatakan bahwa yang menjadikan sebuah khabar shadiq demikian dapat dipercaya adalah karena ia diriwayatkan dari generasi ke generasi dengan mata rantai periwayatan yang otentik.
Al-Qur’an berikut hadits shahih adalah contoh terbaik perwujudan dari khabar shadiq tersebut. Artinya, terutama dalam kasus al-Qur’an, salah satu kriteria minimal dan utama seseorang disebut Muslim adalah kepercayaannya terhadap kebenaran al-Qur’an.
Bagi seorang muallaf, sebagai contoh, al-Qur’an dengan segala informasi yang diberitakan di dalamnya tidak lain adalah sebuah kitab dengan sekumpulan berita yang boleh jadi terasa asing baginya.
Namun, faham atau tidak faham, sudah terbukti kebenarannya atau belum, ia harus meyakini sedari awal bahwa segala yang terkandung dalam kitab tersebut adalah benar adanya. Tanpa keyakinan tersebut maka ia tidak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim. Berita benar yang datang dari luar dirinya itulah yang dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai pengetahuan ‘ilm al-yaqin.
Sedemikian kuat validitas al-Qur’an, terutama teksnya, karena transmisinya menggunakan satu sistem yang disebut mutawatir. Yaitu, model periwayatan yang dilakukan oleh sekian banyak orang dari generasi ke generasi. Selain itu, para periwayat tersebut hampir dipastikan mustahil untuk berbohong terkait validitas berita yang diriwayatkan tersebut.
Dalam konteks al-Takatsur ayat 5, keberadaan neraka Jahim jelas termaktub dalam al-Qur’an. Meskipun seorang Muslim belum pernah melihatnya, namun ia harus percaya sepenuhnya terhadap keberadaannya. Semata-mata karena ia merupakan bagian dari informasi bernama khabar shadiq tersebut; al-Qur’an. Begitu pula dalam konteks Jepang. Jamak diketahui betapa masif orang-orang dari dekade ke dekade memberitakan tentang keberadaan negeri bernama ‘Jepang’. Baik melalui siaran televisi, radio, penerbitan buku, majalah, dan koran.
Sedemikian masif ‘periwayatan’ informasi ini sehingga hampir mustahil menemukan seseorang di era modern ini yang tidak percaya bahwa negara bernama ‘Jepang’ sesungguhnya ada. Artinya, meski belum pernah ke Jepang, ia tetap bisa meyakini bahwa Jepang memang nyata ada. Periwayatan masif-otentik seperti inilah yang ingin saya sebut sebagai rasionalisasi dari khabar shadiq.
Artinya juga, konsep khabar shadiq sesungguhnya bukan mitos yang hanya berlaku pada urusan teologi sehingga tidak bisa dipercaya. Namun dalam perkara keseharian pun, kita dapat dengan mudah menemukan simplifikasinya.
Walhasil, ‘ilm al-yaqin adalah pengetahuan yang bersandar pada kemampuan nalar. Nalar memang pada dasarnya bersumber pada akal. Namun, dengan nalar itu juga kita dapat merasionalisasi apa yang disebut khabar shadiq.
Transit di Narita ternyata tidak hanya memberi waktu kepada kami untuk melakukan jeda penerbangan. Tapi juga memaksa saya untuk melakukan jeda pemikiran; menalar ‘ilm al-yaqin. Wallahu A’lam.
Penulis: Muhammad Abdul Aziz, Peserta Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) Jakarta; Visiting PhD Researcher di Hartford International University for Religion and Peace.
Terkini
Lihat Semua