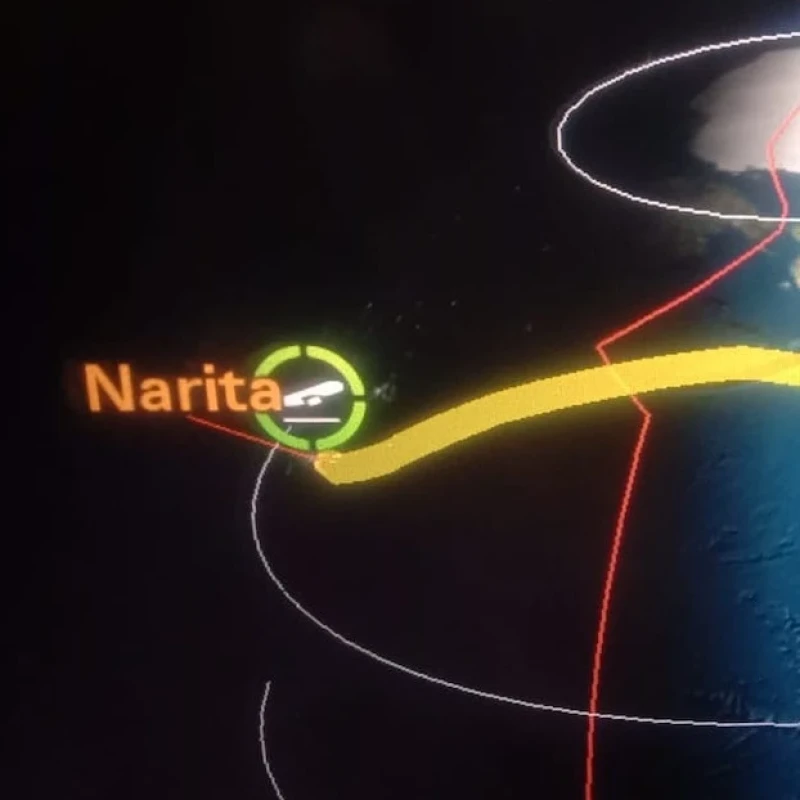Belajar Islam di Hartford (4): Fiqh al-Aqalliyyat atau Fiqh al-Adhalliyyat? (1)
Kamis, 22 Februari 2024 | 13:15 WIB
Beberapa bulan kemarin, dalam kesempatan menghadiri pengajian bulanan di daerah New Britain yang masih merupakan kawasan Hartford, Connecticut, Amerika Serikat, saya bertemu dengan seseorang. Berbadan tinggi besar, dengan jambang putih dibiarkan mengitari dagu dan rahang, saya mengira beliau berasal asli dari Amerika Serikat. Namun beliau mengonfirmasi bahwa dirinya berasal dari Yordania. Istrinya adalah seorang wanita asal Indonesia.
Menarik sekali berbicara dengan beliau. Sebab, ternyata beliau sangat akrab dengan studi keislaman. Sebab, meski berasal dari Arab, seseorang tidak lantas bisa begitu saja akrab dengan materi keislaman. Dan bapak berjambang putih tersebut adalah orang Arab yang begitu fasih dalam literatur keislaman.
Sedemikian menarik sehingga pembicaraan mengalir begitu saja tanpa terasa. Namun, sampai pada satu titik ketika saya sebutkan saya sedang belajar di Hartford International University (HIU), air muka beliau menjadi berubah.
“Why do you study at Hartford Seminary (sebutan lama untuk Hartford International University (HIU) tempat saya belajar sekarang)? What are you looking for?” (Mengapa kamu belajar di Hartford Seminary? Apa yang sedang kamu cari?)
Rupanya beliau meragukan HIU. Bahkan pada satu titik beliau juga mengatakan bahwa kurikulum dan kegiatan akademik di seminari-seminari itu sesungguhnya dilakukan lebih untuk mendiskreditkan Islam. Mendengar penuturan ini, saya teringat pesan (alm) Prof. Dr. Azyumardi Azra. Waktu itu, pada tahun 2017, untuk keperluan pengambilan data tesis, saya sedang mewancarai beliau di kantornya, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kantor yang lima tahun kemudian ternyata justru saya lewati hampir tiap hari. Sebab saya kini tinggal di Ciputat, tepat di depan UIN Kampus 1.
Beliau menyatakan bahwa sebagian umat Islam hari ini terkena apa yang disebut besieged mentality, yaitu mental terkepung. Mereka selalu merasa sedang dimusuhi, dicurigai, dan dikepung dengan aneka konspirasi. Terhadap pendapat tersebut, saya fikir memang kita semua harus cermat dan berhati-hati. Dalam hal ini, nasihat Rasulullah Saw terhadap para sahabat dan ummatnya ketika mendengar cerita-cerita dari Yahudi patut untuk dipertimbangkan: “la tushaddiqu ahl al-kitab wa la tukadzdzibuhum” (jangan dibenarkan semuanya; termasuk juga jangan didustakan semuanya).
Artinya, pendapat tentang mental terkepung tersebut boleh jadi mengandung kebenaran; namun juga berpotensi mengandung kesalahan. Dalam posisi demikian, maka nasihat lain – kali ini dari al-Qur’an – patut juga untuk dipertimbangkan: “wa la taqfu ma laisa laka bihi ‘ilm” (jangan mengikuti – atau dalam hal ini mengatakan – apa yang tidak kamu ketahui sesungguhnya).
Jika memang satu pendapat terbukti salah, maka tidak salah jika ia divonis salah. Yang tidak boleh adalah mudah-mudah mengatakan atau bahkan menuduh buruk seseorang berdasarkan apa yang sesungguhnya kita belum atau tidak mengetahui secara persis. Kembali pada bapak berkelahiran Yordania di atas, satu hal lain yang tidak kalah seru adalah ketika pembahasan sampai pada fiqh al-aqalliyyat, satu bidang yang menjadi bagian dari disertasiku. Air muka beliau berubah menandakan ketidaksetujuan.
Hakikat Fiqh al-Aqalliyyat
“Apa itu fiqh al-aqalliyyat?” tandasnya mempertanyakan. Saya kemudian sedikit uraikan bahwa fiqh al-aqalliyyat adalah satu disiplin relatif baru dalam bidang fiqh yang didedikasikan untuk memberikan jalan keluar atas berbagai kesulitan hidup (hardship) yang dijalani umat Islam khususnya mereka yang hidup sebagai minoritas.
Dalam hal ini, hampir seluruh sarjana sepakat bahwa mereka yang sekarang ini hidup di Barat dapat tergolong sebagai Muslim minoritas. Status tersebut melahirkan satu fakta bahwa berbagai kebijakan pemerintahan dan struktur sosial yang ada belum mendukung mereka sepenuhnya untuk menjalankan kewajiban diri sebagai seorang Muslim.
Pencetus fikih ini ada dua yaitu Taha Jabir al-Alwani dengan bukunya Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections (2003). Sebenarnya beberapa tahun sebelum tahun terbit buku tersebut, pada 1994, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Fiqh Council of North America, al-Alwani sudah menelurkan gagasan fiqh tersebut. Berdasarkan gagasan tersebut, al-Alwani yang meraih seluruh jenjang akademiknya dari S1 hingga S3 di Universitas al-Azhar ini mengeluarkan fatwa diperbolehkannya bagi umat Islam di Amerika Serikat untuk ikut serta dalam pemilihan umum bahkan kegiatan militer negara.
Tokoh kedua yang dianggap sebagai pendiri fiqh al-aqalliyyat adalah Yusuf al-Qaradlawi. Secara praktis, pada 1997, ia mendirikan European Council for Fatwa and Research yang dimaksudkan untuk memberikan solusi keagamaan bagi umat Islam yang ada di Eropa. Empat tahun setelahnya baru kemudian ia menguraikan secara teoritis dan komprehensif bagaimana bentuk fiqh minoritas dalam karyanya Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah (2001).
Dari sini dapat kemudian diketahui bahwa tesis utama fiqh al-aqalliyyat adalah merealisasikan sebuah visi Islam: berusaha mengurangi segala kesulitan (raf’u al-haraj). Diakui atau tidak, jika dibandingkan dengan yang hidup di negara-negara mayoritas Muslim, umat Islam yang ada di Barat menghadapi kesulitan lebih banyak dalam menjalankan tanggung jawab dirinya sebagai seorang Muslim. “Itu bukan fiqh al-aqalliyyat, tapi fiqh al-adhalliyyat (fikih kesesatan),” cetus bapak asal Yordani itu menyergap.
“Seumur-umur saya belajar fiqh dan usul al-fiqh, baru kali ini saya mendengar ada yang memplesetkan fiqh al-aqalliyyat menjadi fiqh al-adhalliyyat,” gumamku dalam hati.
Sejatinya, ketika beliau menganggap bahwa fiqh al-aqalliyyat tersebut tidak lain kecuali membawa kesesatan, saya agak kehilangan keseimbangan berpikir beberapa detik. Saya tidak pernah membayangkan sedikit pun akan ada pemlesetan seperti itu. Saya merasa sebelumnya bahwa kebutuhan terhadap disiplin ini memang sudah diakui oleh hampir – jika bukan semua – sarjana.
Sebab, bagi saya sendiri yang sudah merasakan hidup di Amerika Serikat meski hanya beberapa bulan, kesulitan yang dialami kaum Muslim minoritas tampak nyata. Jumlah masjid demikian terbatas sehingga salat Jum’at diselenggarakan bahkan hingga tiga kali dalam satu hari. Tidak semua tempat umum juga menyediakan tempat salat sehingga kadang kita pun harus salat di toilet – yang bersih. Infrastruktur sebagian masjid pun tidak menyediakan tempat yang memadai untuk membasuh kaki ketika wudhu sehingga yang dibasuh pun kaos kaki (khuffah). Yang kemudian disorot oleh bapak asal Yordania tersebut adalah tentang diperbolehkannya dalam fiqh al-aqalliyyat penggunaan bank-bank konvensional. Beliau berpendapat bahwa seorang Muslim hendaknya dalam kehidupan kesehariannya tidak menggunakan transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba sebagaimana hal ini dianggap nyata ada dalam bank-bank konvensional tersebut. Ketentuan seperti inilah yang agaknya kemudian menggiringnya pada kesimpulan bahwa fiqh al-aqalliyyat tidak lain justru menggiring seorang Muslim pada kesesatan.
Dengan pendapat ini, saya kemudian menyadari mengapa beliau begitu anti terhadap Yusuf al-Qaradlawi. Sebab, al-Qaradlawi memang berkontribusi dalam menerbitkan satu fatwa tentang dibolehkannya penggunaan terbatas terhadap bank-bank konvensional untuk umat Islam yang ada di Barat. Dalam konteks ini, pembolehan tersebut dimaksudkan dalam kasus pembelian kredit rumah yang menurutnya memang sesuatu yang urgen bagi kehidupan seorang Muslim – bahkan siapa saja dari anak manusia.
Saya kemudian juga menjadi paham mengapa dalam pembicaraan tersebut, beliau berulang kali menyebut nama ‘Said Ramadhan al-Buthi’’, seorang ulama asal Syiria. Sebagaimana diketahui oleh khalayak bahwa al-Buthi memang dalam beberapa persoalan dikenal berbeda pandangan dengan al-Qaradlawi.
Dalam kasus pembolehan al-Qaradlawi terhadap penggunaan bank-bank konvensional yang mengandung unsur riba, disebutkan oleh al-Buthi bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan. Sebab, lanjutnya, al-Qaradlawi sendiri jelas mewarisi pemikiran dan ideologi al-Ikhwan al-Muslimin. Berbagai fatwa yang dikeluarkannya adalah dimaksudkan untuk memuaskan kepentingan masyarakat Barat yang sesungguhnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Islam. Islam, al-Buthi berargumen, sesungguhnya tidak membeda-bedakan antara Muslim satu dengan lainnya sehingga harus ada istilah minoritas dan mayoritas (Al-Jazeera).
Tentu saja saya amat hormat dengan al-Buthi. Ia adalah penulis kitab berjudul Al-Hikam al-Atha’iyyah: Syarh wa Tahlil, yang merupakan syarahan berjumlah lima jilid terhadap kitab Al-Hikam karangan Ibnu Atha’illah al-Sakandari yang fenomenal itu. Kitab syarahan ini saya gunakan selama ini – sebelum mengikuti short course – untuk mengisi kajian bulanan di Masjid Baitut Tarbiyah di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat. Pada saat yang sama, tentu juga saya menaruh respek yang dalam terhadap al-Qaradlawi. Ia merupakan tokoh sentral – selain Prof. Quraish Shihab – yang saya kupas pemikirannya dalam disertasi saya.
Dari gaya pembicaraannya, saya mendapat kesan bahwa memang Bapak asal Yordania tersebut memang akrab dengan literatur keislaman. Awalnya saya mengira beliau adalah seorang dai atau dosen dalam bidang Islamic studies. Namun dikatakan olehnya bahwa minatnya pada Islam merupakan keinginan pribadi dan dipenuhi melalui pendidikan non-formal.
Beliau juga akrab dengan pemikiran berbagai tokoh dan sarjana Muslim. Namun, beliau mengaku tidak menyukai Yasir Qadhi – di antara sosok yang saya kagumi. Ulama Amerika keturunan Pakistan ini dianggap terlalu banyak bicara; namun apa yang dibicarakannya bukanlah sesuatu yang esensial.
“Let me listen to one who is speaking. In only over five minutes. I will immediately know who he really is,” katanya.
Maksudnya, ketika mendengar seseorang berbicara, dalam hanya lima menit, beliau akan tahu orang tersebut berakidah apa, beraliran apa, kadar pengetahuan, dan corak pemikirannya.
Pembicaraan dengan beliau, meski dalam beberapa hal kami tidak saling setuju, amat berkesan. Karena itu, demi mendapatkan pemahaman yang moderat, terutama dalam konteks ketidaksetujuannya dengan konsep fiqh al-aqalliyyat, berikut adalah usaha saya untuk mendudukkan di mana sesungguhnya posisi fiqh al-aqalliyyat sehingga ia dianggap urgen untuk hadir di masa kontemporer ini. [bersambung]
Muhammad Abdul Aziz, peserta Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) Jakarta.
Terpopuler
1
MAPABA PMII STFI Sadra Dorong Kaderisasi Berbasis Intelektual dan Spiritual
2
Yayasan Anak Nagari Indonesia Rayakan HUT ke-80 RI dengan Lomba Tradisional dan Edukatif
3
MUI Jakarta: Perbedaan adalah Sunnatullah yang Harus Diterima
4
MWCNU Cempaka Putih Gelar Diklat Standarisasi Mu’allim Al-Qur’an
5
Waspada Brain Rot, Dampak Konsumsi Konten Digital Instan
6
STKQ Al-Hikam Gelar Raker 2025 Bahas Penguatan Tridharma
Terkini
Lihat Semua